
Raden Ngabehi Ronggowarsito (lahir:Surakarta,1802 – wafat:Surakarta, 1873) adalah pujangga besar budaya Jawa yang hidup diKasunana Surakarta. Ia dianggap sebagai pujangga terakhir tanah Jawa.
Asal-Usul
Nama aslinya adalah '''Bagus Burham'''. Lahir di Surakarta tanggal 15 Maret 1802. Merupakan putra dari Mas Pajangswara putra Yasadipura II putra Yasadipura I, pujangga besar Kasunanan Surakarta.
Ayah Bagus Burham merupakan keturunan Kesultanan Pajang sedangkan ibunya adalah keturunan Kesultanan Demak. Bagus Burham juga memiliki seorang pengasuh setia bernama Ki Tanujoyo.
Riwayat Masa Muda
Sewaktu kecil Burham terkenal nakal dan gemar judi. Ia dikirim kakeknya untuk berguru agama Islam pada Kyai Imam Besari pemimpin Pesantren Gebang.
Cetak tebalinatar di desa Tegalsari (Ponorogo). Pada mulanya ia tetap saja bandel, bahkan sampai kabur ke Madiun. Setelah kembali ke Ponorogo, konon, ia mendapat “pencerahan” di Sungai Kedung Watu, sehingga berubah menjadi pemuda alim yang pandai mengaji.
Ketika pulang ke Surakarta, Burham diambil sebagai cucu angkat Panembahan Buminoto (adik Pakubuwana IV). Ia kemudian diangkat sebagai Carik Kadipaten Anom bergelar Mas Pajanganom tanggal 28 Oktober 1819.
Pada masa pemerintahan Pakubuwana V (1820 – 1823), karir Burham tersendat-sendat karena raja baru ini kurang suka dengan Panembahan Buminoto yang selalu mendesaknya agar pangkat Burham dinaikkan.
Pada tanggal 9 November 1821 Burham menikah dengan Raden Ayu Gombak dan ikut mertuanya, yaitu Adipati Cakradiningrat di Kediri. Di sana ia merasa jenuh dan memutuskan berkelana ditemani Ki Tanujoyo. Konon, Burham berkelana sampai ke pulau Bali di mana ia mempelajari naskah-naskah sastra Hindu koleksi Ki Ajar Sidalaku.
Puncak Kejayaan Karir
Bagus Burham diangkat sebagai Panewu Carik Kadipaten Anom bergelar Raden Ngabei Ronggowarsito, menggantikan ayahnya yang meninggal di penjara Belanda tahun 1830. Lalu setelah kematian kakeknya (Yasadipura II), Ranggawarsita diangkat sebagai pujangga keraton Surakarta oleh Pakubuwana VII pada tanggal 14 September 1845.
Pada masa inilah Ranggawarsita melahirkan banyak karya sastra. Hubungannya dengan Pakubuwana VII juga sangat harmonis. Ia juga dikenal sebagai peramal ulung dengan berbagai macam ilmu kesaktian.
Naskah-naskah babad cenderung bersifat simbolis dalam menggambarkan keistimewaan Ranggawarsita. Misalnya, ia dikisahkan mengerti bahasa binatang. Ini merupakan simbol bahwa, Ranggawarsita peka terhadap keluh kesah rakyat kecil.
Misteri Kematian
Pakubuwana IX naik takhta sejak tahun 1861. Ia adalah putra Pakubuwana VI yang dibuang ke Ambon tahun 1830 karena mendukung Pangeran Diponegoro. Konon, sebelum menangkap Pakubuwana VI, pihak Belanda lebih dulu menangkap juru tulis keraton, yaitu Mas Pajangswara untuk dimintai kesaksian. Meskipun disiksa sampai tewas, Pajangswara tetap diam tidak mau membocorkan hubungan Pakubuwana VI dengan Pangeran Dipanegara.
Meskipun demikian, Belanda tetap saja membuang Pakubuwana VI dengan alasan bahwa Pajangswara telah membocorkan semuanya. Fitnah inilah yang menyebabkan Pakubuwana IX kurang menyukai Ranggawarsita, yang tidak lain adalah putra Pajangswara.
Hubungan Ranggawarsita dengan Belanda juga kurang baik. Meskipun ia memiliki sahabat dan murid seorang indo bernama C.F. Winter sr., namun gerak-geriknya tetap saja diawasi Belanda. Ranggawarsita dianggap sebagai jurnalis berbahaya yang tulisan-tulisannya dapat membangkitkan semangat juang kaum pribumi. Karena suasana kerja yang semakin tegang, akibatnya Ranggawarsita pun keluar dari jabatan redaksi surat kabar Bramartani tahun 1870.
Ranggawarsita meninggal dunia secara misterius tanggal 24 Desember 1873. Anehnya, tanggal kematian tersebut justru terdapat dalam karya terakhirnya, yaitu ''Serat Sabdajati'' yang ia tulis sendiri. Hal ini menimbulkan dugaan kalau Ranggawarsita meninggal karena dihukum mati, sehingga ia bisa mengetahui dengan persis kapan hari kematiannya.
Penulis yang berpendapat demikian adalah Suripan Sadi Hutomo (1979) dan Andjar Any (1979). Pendapat tersebut mendapat reaksi keras, terutama dari pihak [[keraton Surakarta]]. Berbagai pendapat ditujukan untuk membantah bahwa Ranggawarsita bukan mati dibunuh. Mereka tetap yakin kalau Ranggawarsita adalah peramal ulung sehingga tidak aneh kalau ia dapat meramal hari kematiannya sendiri. Pendapat kedua penulis dianggap merendahkan kehebatan mata batin Ranggawarsita.
Kedua penulis tetap teguh pada pendapat mereka dengan disertai alasan-alasan logis, bahwa Ranggawarsita meninggal karena dihukum mati. Padahal waktu itu yang berhak menjatuhi hukuman mati hanyalah pemerintah Hindia Belanda. Jika benar demikian, hukuman mati ini justru meningkatkan derajat Ranggawarsita di mata rakyat, karena pihak Belanda menganggapnya sebagai tokoh berbahaya yang harus disingkirkan.
Ranggawarsita dimakamkan di Desa Palar, kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Makamnya pernah dikunjungi dua presiden Indonesia yaitu Presiden Soekarno dan Gus Dur pada masa mereka menjabat.
Ranggawarsita dan Zaman Edan
Istilah Zaman Edan konon pertama kali diperkenalkan oleh Ranggawarsita dalam ''Serat Kalatida'', yang terdiri atas 12 bait tembang Sinom. Salah satu bait yang paling terkenal adalah:
:''amenangi jaman édan,
:''éwuhaya ing pambudi,
:''mélu ngédan nora tahan,
:''yén tan mélu anglakoni,
:''boya keduman mélik,
:''kaliren wekasanipun,
:''ndilalah kersa Allah,
:''begja-begjaning kang lali,
:''luwih begja kang éling klawan waspada''.
yang terjemahannya sebagai berikut:
:''menyaksikan zaman gila,
:''serba susah dalam bertindak,
:''ikut gila tidak akan tahan,
:''tapi kalau tidak mengikuti (gila),
:''tidak akan mendapat bagian,
:''kelaparan pada akhirnya,
:''namun telah menjadi kehendak Allah,
:''sebahagia-bahagianya orang yang lalai,
:''akan lebih bahagia orang yang tetap ingat dan waspada.''
Syair di atas menurut analisis seorang penulis bernama Ki Sumidi Adisasmito adalah ungkapan kekesalan hati pada masa pemerintahan Pakubuwono IX yang dikelilingi para penjilat yang gemar mencari keuntungan pribadi. Syair tersebut masih relevan hingga zaman modern ini di mana banyak dijumpai para pejabat yang suka mencari keutungan pribadi tanpa memedulikan kerugian pihak lain.
Karya Sastra
Karya sastra tulisan Ranggawarsita antara lain,
* ''Bambang Dwihastha'' : cariyos Ringgit Purwa
* ''Bausastra Kawi'' atau ''Kamus Kawi – Jawa'', beserta C.F. Winter sr.
* ''Sajarah Pandhawa lan Korawa : miturut Mahabharata'', beserta C.F. Winter sr.
* ''Sapta dharma''
* ''[[Serat Aji Pamasa]]''
* ''[[Serat Candrarini]]''
* ''Serat Cemporet''
* ''[[Serat Jaka Lodang]]''
* ''[[Serat Jayengbaya]]''
* ''[[Serat Kalatidha]]''
* ''[[Serat Panitisastra]]''
* ''[[Serat Pandji Jayeng Tilam]]''
* ''[[Serat Paramasastra]]''
* ''[[Serat Paramayoga]]''
* ''[[Serat Pawarsakan]]''
* ''[[Serat Pustaka Raja]]''
* ''[[Suluk Saloka Jiwa]]''
* ''[[Serat Wedaraga]]''
* ''[[Serat Witaradya]]''
* ''[[Sri Kresna Barata]]''
* ''[[Wirid Hidayat Jati]]'
* [[Wirid Ma'lumat Jati]]''
Ramalan tentang Kemerdekaan Indonesia
Ranggawarsita hidup pada masa penjajahan Belanda. Ia menyaksikan sendiri bagaimana penderitaan rakyat Jawa, terutama ketika program Tanam Paksa dijalankan pasca Perang Diponegoro. Dalam suasana serba memprihatinkan itu, Ranggawarsita meramalkan datangnya kemerdekaan, yaitu kelak pada tahun ''Wiku Sapta Ngesthi Janma''.
Kalimat yang terdiri atas empat kata tersebut terdapat dalam ''Serat Jaka Lodang'', dan merupakan kalimat Suryasengkala yang jika ditafsirkan akan diperoleh angka 7-7-8-1. Pembacaan Suryasengkala adalah dibalik dari belakang ke depan, yaitu 1877 Saka, yang bertepatan dengan 1945 Masehi, yaitu tahun kemerdekan Republik Indonesia.
Pengalaman pribadi [[Presiden Soekarno]] pada masa penjajahan adalah ketika berjumpa dengan para petani miskin yang tetap bersemangat di dalam penderitaan, karena mereka yakin pada kebenaran ramalan Ranggawarsita tentang datangnya kemerdekaan di kemudian hari.
meskipun perjuangannya tidak menggunakan pedang atau senapan, melainkan menggunakan tinta yang sanggup membangkitkan semangat kaum pribumi dan meresahkan pemerintah Hindia Belanda.
Serat Jaka Lodang
adalah syair/karangan dalam bahasa Jawa dari pujangga Rangga Warsita yang mengandung petuah akan adanya suatu jaman yang penuh dengan pancaroba.
Serat Jaka Lodang ini terdiri dari dua bagian: bagian pertama dalam bentuk gambuh dengan 3 bait/paragraf (masing-masing mengandung 5 baris) dan bagian kedua dalam bentuk sinom . ...
Pada bagian kedua yang juga terdiri dari 3 bait (masing-masing mengandung 9 baris), terdapat petuah sebagai berikut (beserta terjemahan bebas bahasa Indonesianya):
Sasedyane tanpa dadya
Sacipta-cipta tan polih
Kang reraton-raton rantas
Mrih luhur asor pinanggih
Bebendu gung nekani
Kongas ing kanistanipun
Wong agung nis gungira
Sudireng wirang jrih lalis
Ingkang cilik tan tolih ring cilikira
Suatu waktu seluruh kehendak tidak ada yang terwujud,
apa yang dicita-citakan akan berantakan,
apa yang dirancang menjadi gagal,
yang ingin menang malah kalah,
karena datangnya hukuman yang berat dari Tuhan.
Yang tampak hanyalah perbuatan-perbuatan tercela,
orang besar akan kehilangan kebesarannya,
lebih baik nama tercemar daripada bertanggung jawab (mati),
sedangkan yang kecil juga tidak mau tahu akan keterbatasannya.
Wong alim-alim pulasan
Njaba putih njero kuning
Ngulama mangsah maksiat
Madat madon minum main
Kaji-kaji ambataning
Dulban kethu putih mamprung
Wadon nir wadorina
Prabaweng salaka rukmi
Kabeh-kabeh mung marono tingalira
Banyak orang yang alim, tetapi hanyalah bersifat hiasan saja,
diluar tampak baik (putih) tetapi di dalamnya kuning,
banyak ulama berbuat maksiat,
mengisap ganja, berbuat selingkuh, minum minuman keras, berjudi.
Banyak haji melemparkan,
dan melepas ikat kepala hajinya,
para wanita kehilangan kewanitaannya,
karena pengaruh harta benda,
semuanya itu hanya kebendaan-lah yang menjadi tujuannya.
Para sudagar ingargya
Jroning jaman keneng sarik
Marmane saisiningrat
Sangsarane saya mencit
Nir sad estining urip
Iku ta sengkalanipun
Pantoging nandang sudra
Yen wus tobat tanpa mosik
Sru nalangsa narima ngandel ing suksma
Di antara para saudagar dan pedagang,
hanya harta bendalah yang dihormati pada jaman itu,
seluruh isi dunia penuh dengan penderitaan,
kesengsaraan makin menjadi-jadi,
di tahun Jawa 1860 (Nir=0, Sad=6, Esthining=8, Urip=1) atau 1930 Masehi
yang akan menjadi tonggak sejarahnya.
Pada akhirnya penderitaan yang akan terjadi,
pada saat semua mulai bertobat dan menyerahkan diri,
kepada kekuasaan Tuhan dengan sepenuh hati.
Serat Jayengbaya
adalah buku petuah / falsafah kehidupan yang dikarang oleh R. Ngabehi Rangga Warsita dan diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta pada tahun 1988 dengan alih bahasa dan alih aksara L. Mardiwarsito. Buku ini dikarang oleh R. Ngabehi Ranggawarsita pada saat beliau berumur antara 20 sampai 28 tahun sewaktu menjadi carik Kadipaten Anom di Kasunanan Surakarta .
Buku serat ini menceritakan tentang seorang tokoh bernama Jayengbaya yang ingin mencari kebahagiaan dalam kehidupannya dengan cara melaksanakan tugas sebaik-baiknya, dengan mencari jabatan tinggi, dan mengejar kedudukan yang terhormat. Dalam usaha ini, 47 macam cara kehidupan telah dicobanya, tetapi tidak ada satupun yang cocok baginya, karena masing-masing cara kehidupan tersebut selalu ada yang mengandung kekurangan-kekurangan dan tidak ada satu pun yang sempurna. Akhirnya, Jayengbaya memutuskan untuk kembali menekuni cara kehidupannya yang semula, karena hal itulah yang dianggap paling baik baginya.
Asmaradana:
Kidung kadresaning kapti
Yayah nglamong tanpa mangsa
Hingan silarja jatine
Satata samaptaptinya
Raket rakiting ruksa
Tahan tumaneming siku
Karasuk sakeh kasrakat.
Yang secara umum dapat diterjemahkan menjadi:
Inilah nyanyian tentang ketabahan hati
Seakan berkicau tanpa mengenal waktu
Tanpa mengenal batas kesusilaan dan keselamatan,
Oleh karenanya kita harus selalu waspada
dalam menghadapi hukum alam
dan kuat dalam mengendalikan emosi
dan dalam menghadapi penderitaan yang dialami.
Serat Kalatidha
Serat Kalatidha atau Kalatidha saja adalah sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa karangan Raden Ngabehi Rangga Warsita berbentuk tembang macapat. Karya sastra ini ditulis kurang lebih pada tahun 1860 Masehi. Kalatidha adalah salah satu karya sastra Jawa yang ternama. Bahkan sampai sekarang banyak orang Jawa terutama kalangan tua yang masih hapal paling tidak satu bait syair ini.
Latar belakang
''Kalatidha'' bukanlah karya Rangga Warsita yang terpanjang. Syair ini hanya terdiri dari 12 bait dalam metrum Sinom. ''Kala tidha'' secara harafiah artinya adalah "zaman gila" atau ''jaman édan'' seperti ditulis oleh Rangga Warsita sendiri. Konon Rangga Warsita menulis syair ini ketika pangkatnya tidak dinaikkan seperti diharapkan. Lalu ia menggeneralisir keadaan ini dan ia anggap secara umum bahwa zaman di mana ia hidup merupakan zaman gila di mana terjadi krisis. Saat itu Rangga Warsita merupakan pujangga kerajaan di Keraton Kasunanan Surakarta. Ia adalah ''pujangga panutup'' atau "pujangga terakhir". Sebab setelah itu tidak ada "pujangga kerajaan" lagi.
== Arti singkat ==
Syair ''Kalatidha'' bisa dibagi menjadi tiga bagian: bagian pertama ialah bait 1 sampai 6, bagian kedua ialah bait 7 dan bagian kedua ialah bait 8 sampai 12. Bagian pertama ialah tentang keadaan masa Rangga Warsita yang menurut ialah tanpa prinsip. Bagian kedua isinya ialah ketekadan dan sebuah introspeksi diri. Sedangkan bagian ketiga isinya ialah sikap seseorang yang taat dengan agama di dalam masyarakat.
Bait Serat Kalatidha yang paling dikenal adalah bait ke-7. Sebab bait ini adalah esensi utama syair ini. Amanat syair ini bisa diringkas dalam satu bait ini.
Amenangi jaman édan, Menyaksikan zaman gila,
éwuhaya ing pambudi, serba susah dalam bertindak,
mélu ngédan nora tahan, ikut gila tidak akan tahan,
yén tan mélu anglakoni, tapi kalau tidak mengikuti (gila),
boya kéduman mélik, tidak akan mendapatkan bagian,
kaliren wekasanipun, kelaparan pada akhirnya,
ndilalah kersa Allah, namun telah menjadi kehendak Allah,
begja-begjaning kang lali, sebahagia-bahagianya orang yang lalai,
luwih begja kang éling klawan waspada. akan lebih bahagia orang yang tetap ingat dan waspa
Rabu, Mei 07, 2008
Ronggowarsito
Langganan:
Posting Komentar (Atom)











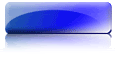

Tidak ada komentar:
Posting Komentar